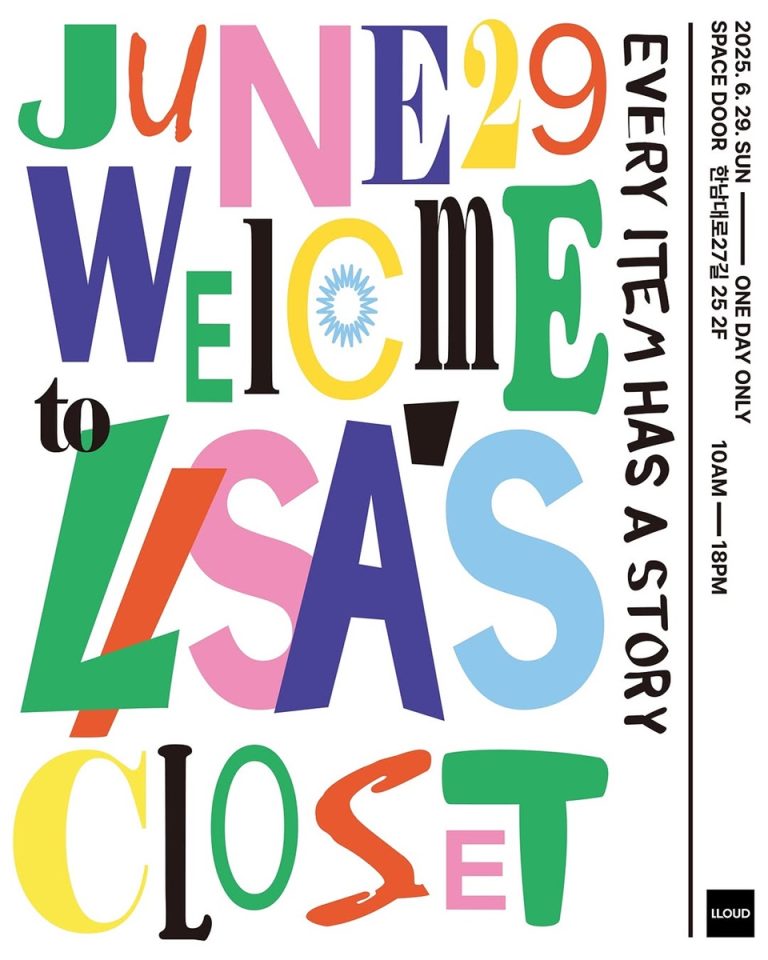Di balik lonjakan jumlah lembaga zakat dan yayasan kemanusiaan di Indonesia selama dua dekade terakhir, satu pertanyaan mendasar tetap menggantung, bagaimana merawat kepercayaan publik agar potensi donasi benar-benar optimal dan berdampak luas? Untuk menjawabnya, Turki sering dijadikan rujukan menarik. Hal ini bukan hanya karena reputasi lembaga-lembaga seperti IHH Humanitarian Relief Foundation, Turkish Red Crescent (Kızılay), dan sistem wakaf produktif Suleymaniye, tetapi juga karena Diplomasi Kemanusiaan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Turki. Melalui diplomasi ini, lahir praktik-praktik yang mampu menyeimbangkan kepentingan nasional, nilai keagamaan, dan aksi nyata kemanusiaan lintas benua.
Di Indonesia, pertumbuhan lembaga kemanusiaan dan organisasi zakat dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang sangat signifikan. Berdasarkan data Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), potensi zakat nasional diperkirakan melebihi Rp 327 triliun per tahun (Baznas Outlook Zakat Indonesia 2023). Namun, realisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah baru mencapai sekitar Rp 28–30 triliun per tahun pada 2022–2023, tersebar di ratusan lembaga zakat resmi, lembaga filantropi Islam, dan yayasan sosial independen. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah yayasan sosial dan lembaga kemanusiaan terus tumbuh rata-rata 5–10% setiap tahun, terutama pasca era reformasi, bencana besar seperti tsunami Aceh, dan pandemi COVID-19.
Pertumbuhan ini tentu menjadi kabar baik, mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat Indonesia. Namun, di balik optimisme itu, tantangan besar tetap ada yakni bagaimana menjaga kepercayaan publik agar potensi zakat dan donasi dapat dihimpun secara optimal, didistribusikan tepat sasaran, dan dikelola dengan transparan. Kasus penyelewengan dana, minimnya pelaporan, dan rendahnya loyalitas donatur masih menjadi catatan serius.
Di tengah tantangan tersebut, Turki kerap dijadikan contoh bagaimana sebuah negara yang berhasil membangun ekosistem filantropi berbasis kepercayaan publik yang kokoh, baik di tingkat lokal maupun internasional. Turki menjadi laboratorium belajar bagi pegiat filantropi global, termasuk Indonesia. Diplomasi Kemanusiaan Turki memungkinkan negara ini menggabungkan kepentingan nasional dengan nilai kemanusiaan, membangun legitimasi internasional, sekaligus meneguhkan identitas domestiknya sebagai bangsa Muslim dengan akar sejarah Ottoman. Dalam praktiknya, Turki berhasil menyinergikan bantuan pemerintah dengan peran aktif LSM dan yayasan Islam, menjadikan upaya kemanusiaannya lebih fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan.
Yang menarik, pendekatan Turki berbeda dengan donor Barat. Alih-alih memaksakan standar liberal, Turki menghormati kedaulatan negara penerima, bekerja sama erat dengan aktor lokal, dan mendasarkan retorika kemanusiaannya pada nilai agama dan sejarah. Pendekatan ini lebih diterima di negara-negara konflik seperti Somalia atau Afghanistan, di mana Turki aktif membangun sekolah, rumah sakit, dan dukungan logistik.
Tiga nama sering dijadikan rujukan di Turki yakni IHH Humanitarian Relief Foundation, Turkish Red Crescent (Kızılay), dan kompleks wakaf Suleymaniye. Ketiganya memiliki sejarah panjang, karakter unik, dan pola manajemen kepercayaan publik yang dapat diadaptasi secara kontekstual.
IHH, misalnya, berawal dari aksi solidaritas lima relawan yang berangkat ke Bosnia pada 1992. Dari langkah sederhana tersebut, IHH berkembang menjadi salah satu NGO kemanusiaan paling berpengaruh di Eropa dan Timur Tengah, beroperasi di lebih dari seratus negara, membangun rumah sakit di zona konflik, dan menyalurkan bantuan ke jutaan penerima manfaat. Kunci keberhasilan mereka terletak pada pelaporan keuangan yang diaudit secara independen, publikasi data penerima manfaat, serta manajemen relawan yang diposisikan sebagai bagian dari keluarga besar lembaga.
Hal serupa diterapkan oleh Turkish Red Crescent atau Kızılay. Sebagai bagian dari jaringan resmi Palang Merah Internasional, Kızılay menyalurkan lebih dari 2,8 juta kantong darah setiap tahun, mendirikan ribuan posko darurat untuk korban gempa dan banjir, serta aktif mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana. Budaya gotong royong dan semangat berdonor memang mengakar dalam masyarakat Turki, tetapi tanpa pengelolaan profesional, kepercayaan publik tidak akan tumbuh sebesar ini.
Di sisi lain, kompleks wakaf Suleymaniye membuktikan bahwa pendanaan berkelanjutan melalui wakaf dapat berjalan ratusan tahun tanpa kehilangan relevansi. Sejak abad ke-16, wakaf Suleymaniye membiayai pendidikan, rumah sakit, dan dapur umum bagi masyarakat miskin. Aset wakaf dikelola secara modern, transparan, dan tetap diaudit agar hasilnya dapat dinikmati lintas generasi.
Apa pelajaran untuk Indonesia? Paling tidak, keterbukaan laporan keuangan dan dampak program menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Manajemen relawan yang manusiawi memastikan program kemanusiaan memiliki tenaga lapangan yang loyal dan berkomitmen jangka panjang. Selain itu, praktik wakaf produktif, seperti di Suleymaniye, bisa menjadi solusi pendanaan berkelanjutan di luar donasi rutin, mengingat potensi aset wakaf di Indonesia yang sangat besar. Tercatat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai lebih dari Rp 180 triliun, meskipun pemanfaatannya masih terbatas.
Tentu saja, praktik baik di Turki tidak dapat diterapkan begitu saja di Indonesia. Struktur sosial, birokrasi, regulasi, dan karakter masyarakat berbeda. Di Turki, zakat dan wakaf telah menjadi budaya turun-temurun yang didukung regulasi dan negara. Di Indonesia, keberagaman agama, birokrasi yang kompleks, dan tantangan literasi keuangan sosial menuntut adaptasi cerdas agar praktik baik benar-benar efektif.
Karena itu, program Studi Lembaga Kemanusiaan Turki yang digagas IFI patut dipandang sebagai pintu belajar. Melalui program ini, pegiat zakat, pengurus yayasan, relawan, dan fundraiser dapat menyaksikan langsung bagaimana IHH membangun jaringan relawan lintas negara, bagaimana Kızılay menanamkan budaya donasi hingga ke akar rumput, dan bagaimana wakaf Suleymaniye tetap produktif ratusan tahun. Diharapkan, semua ini dapat memantik inspirasi agar lembaga kemanusiaan di Indonesia semakin profesional, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan publik yang lebih luas.
Belajar ke Turki bukan berarti meniru mentah-mentah, tetapi menangkap esensi bagaimana kepercayaan publik dibangun melalui laporan terbuka, relawan yang loyal, dan sistem pendanaan yang berkelanjutan. Di era digital, ketika satu kesalahan dapat tersebar dalam hitungan detik, kepercayaan bukan hanya modal, tetapi juga nyawa sebuah lembaga kemanusiaan.
Bagi siapa pun yang peduli pada masa depan filantropi Indonesia, belajar langsung ke Turki adalah investasi pengetahuan dan pengalaman yang layak diperjuangkan. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik harus kita rawat di rumah sendiri melalui kerja nyata yang selalu dapat diuji kapan saja.
Referensi: Baznas Outlook Zakat Indonesia 2023 (baznas.go.id), BPS Data Yayasan Sosial, IHH Humanitarian Relief Foundation (ihh.org.tr), Turkish Red Crescent (Kızılay) (kizilay.org.tr), IFRC Annual Reports (ifrc.org), Waqf System in the Ottoman Empire oleh Baskan & Bagis.